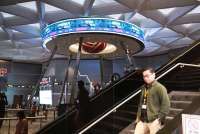Reporter: Harris Hadinata | Editor: Harris Hadinata
KONTAN.CO.ID - SINGAPURA. China bisa mengambil peran untuk menyelesaikan masalah elektrifikasi di kawasan Asia Tenggara. Alasannya, China bisa menekan biaya pengembangan energi.
Gita Wirjawan, Pendiri dan Chairman Ancora Group, menilai kebutuhan energi di Asia Tenggara jauh lebih besar dibanding kemampuan pendanaan yang tersedia. “Energi adalah bentuk ketidaksetaraan,” ujarnya dalam FutureChina Global Forum (FCGF) 2025 di Singapura, Jumat (19/9/2025).
Gita menyebut, di Asia Tenggara, hanya Singapura dan Brunei Darussalam yang sudah mencapai rasio elektrifikasi yang mendukung untuk menjadi negara maju, yakni sekitar 10.000 kWh per kapita. Di urutan berikutnya ada Malaysia dengan rasio elektrifikasi sekitar 5.000 kWh per kapita.
Sementara rasio elektrifikasi Indonesia baru sekitar 3.000 kWh per kapita, setara India. Padahal langkah pertama suatu negara menuju modernisasi adalah rasio elektrifikasi mencapai 6.000 kWh.
Baca Juga: Pengamat Ungkap Strategi untuk Capai Target Rasio Penerimaan Negara 23% PDB
Menurut Gita, untuk menaikkan konsumsi listrik negara di Asia Tenggara selain Singapura dan Brunei Darussalam ke level 6.000 kWh, kawasan ini perlu tambahan kapasitas pembangkit hingga 1 terawatt dari posisi saat ini sekitar 400.000 megawatt.
Biaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut bisa murah bila menggunakan batubara. Tapi, biaya yang dibutuhkan bisa mencapai US$ 2 triliun–US$ 3 triliun bila seluruhnya menggunakan energi baru terbarukan (EBT).
Namun, keterbatasan fiskal di negara-negara Asia Tenggara menjadi kendala besar. Gita mencontohkan Indonesia.
“Tax ratio kita rendah, ruang moneter juga sempit. Rasio pasokan uang terhadap PDB Indonesia hanya 45%, sementara negara maju di atas 200%. Jadi jalan keluar cuma foreign direct investment,” kata Gita.
Baca Juga: Pemerintah Pangkas Rasio Pendapatan Negara 2026, Kemenkeu: Dinamika Semakin Kompleks
Sayangnya, aliran investasi asing langsung ke kawasan masih terbatas, sekitar US$ 200 miliar–230 miliar per tahun. Dari jumlah itu, Singapura menyerap hampir setengahnya.
Sementara Indonesia hanya menyerap US$ 30 miliar–US$ 40 miliar. Dengan pembangunan pembangkit baru sekitar 3.000–5.000 MW per tahun, Indonesia butuh waktu hingga 120 tahun untuk melipatgandakan konsumsi listrik menjadi 6.000 kWh per kapita.
Kondisi ini jelas tidak sejalan dengan target netral karbon 2050–2060. Karena itu, Gita menilai hanya injeksi modal dan teknologi yang bisa mempercepat transisi energi. “Saya percaya China akan jadi pemberi modal paling logis. Mereka bisa menurunkan biaya EBT lebih cepat dibanding negara lain,” ucapnya.


/2024/11/13/2138386407.jpg)