Sumber: Yahoo Finance | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Mantan CEO Microsoft, Steve Ballmer, menyarankan para investor untuk menjaga strategi investasi mereka tetap sederhana.
Menariknya, portofolio investasi Ballmer sendiri mencerminkan filosofi tersebut, dengan lebih dari 80% asetnya berada dalam saham Microsoft dan sisanya dalam reksadana indeks.
"Microsoft telah mengungguli hampir semua aset lain yang mungkin saya miliki," ujar Ballmer kepada Wall Street Journal dalam sesi tanya jawab yang diterbitkan Minggu lalu.
Baca Juga: Daftar 10 Orang Terkaya di Dunia per November 2024: Elon Musk Kokoh di Puncak
"Sulit untuk mengatakan bahwa ini bukan keputusan yang tepat," imbuhnya.
Dalam beberapa tahun terakhir, saham Microsoft memberikan rata-rata imbal hasil sekitar 29% per tahun, termasuk dividen, jauh melampaui rata-rata imbal hasil S&P 500 sebesar 13%.
Lonjakan ini didorong ledakan kecerdasan buatan yang dipicu oleh OpenAI, perusahaan yang didukung oleh Microsoft. Sejak peluncuran ChatGPT pada November 2022, harga saham Microsoft melonjak drastis, membawa kapitalisasi pasarnya melampaui US$ 3 triliun.
Ballmer, yang memimpin Microsoft dari 2000 hingga 2014, mengaku terinspirasi oleh nasihat Warren Buffett bahwa investor ritel lebih baik menanamkan uang mereka di reksadana indeks S&P 500 daripada mencoba mengalahkan pasar.
Baca Juga: Kekayaan Bernard Arnault, CEO Konglomerat Barang Mewah LVMH Rontok
Namun, berbeda dengan Buffett, Ballmer memilih strategi unik dengan portofolio yang sangat terfokus pada satu saham.
Ballmer menjelaskan bahwa ia memutuskan pendekatan tersebut setelah kesulitan menemukan manajer investasi yang secara konsisten mampu mengalahkan pasar.
Dengan kekayaan bersih US$ 151 miliar menurut Bloomberg Billionaires Index, ia dan istrinya kini mengalokasikan dana mereka di reksadana indeks untuk pasar AS dan Eropa, dengan kemungkinan kecil kepemilikan aset di Jepang.
Ia juga mulai mengurangi investasi di ekuitas swasta dan hanya fokus pada saham Microsoft.
"Saya menyukainya. Ini sederhana," ujarnya. "Kami telah sangat diberkati secara finansial. Yang saya cari sekarang adalah menghindari menghabiskan banyak waktu, kecemasan, dan tenaga di bidang yang sudah memberikan imbal hasil rata-rata 7%, seperti S&P 500 dalam jangka panjang."
Baca Juga: Kekayaan Bernard Arnault Menguap Rp 819 Triliun Setelah Saham LVMH Merosot 20%
Saat ditanya mengenai reksadana indeks yang dimilikinya, Ballmer mengaku tidak yakin. Jika bukan S&P 500, maka kemungkinan adalah Russell 2000 atau indeks pasar yang mencerminkan keseluruhan pasar secara luas.
Selain saham, investasi besar lainnya milik Ballmer adalah tim NBA Los Angeles Clippers, yang ia beli pada 2014 seharga US$ 2 miliar. Kini, nilai tim tersebut mencapai US$ 5,5 miliar menurut Forbes.
Untuk para investor ritel, Ballmer menyarankan pendekatan serupa. "Saya akan mengatakan, 'Tetap sederhana'—kecuali jika Anda benar-benar ingin menjadi ahli," ujarnya.
Studi menunjukkan bahwa reksadana indeks yang mengikuti S&P 500 secara konsisten mengungguli sebagian besar dana aktif. Data Morningstar pada Juli mencatat bahwa rata-rata hanya 27% dana aktif yang mampu mengalahkan S&P 500 dalam 10 tahun terakhir.
Baca Juga: Elon Musk Bertahan di Puncak, Ini Daftar 10 Orang Terkaya Dunia Awal September 2024
Portofolio yang terdiversifikasi lintas kelas aset dan geografis juga cenderung tertinggal, dengan hasil yang lebih rendah dibandingkan S&P 500 dalam 13 dari 15 tahun terakhir, menurut Cambria Funds.
Namun, dominasi besar saham-saham teknologi di S&P 500, seperti Microsoft dan Nvidia, membuat investor indeks rentan terhadap penurunan satu saham besar.
Beberapa pihak skeptis di Wall Street memperingatkan bahwa dominasi pasar AS secara global bisa menjadi tanda bahaya.
Baca Juga: Kekayaan Steve Ballmer Capai US$ 120 Miliar, Lebih kaya dari Buffett dan Zuckerberg
"Pembicaraan tentang gelembung di teknologi atau AI, atau strategi investasi yang fokus pada pertumbuhan dan momentum, mengaburkan gelembung terbesar di pasar AS," tulis Ruchir Sharma, ketua Rockefeller International, di Financial Times.
"Amerika terlalu dimiliki, dinilai terlalu tinggi, dan terlalu dibesar-besarkan dalam tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya."


/2011/04/23/1359725803.jpg)


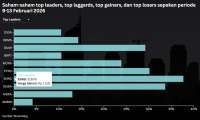








![[Intensive Workshop] Excel for Business Reporting](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_28012616011400.jpg)